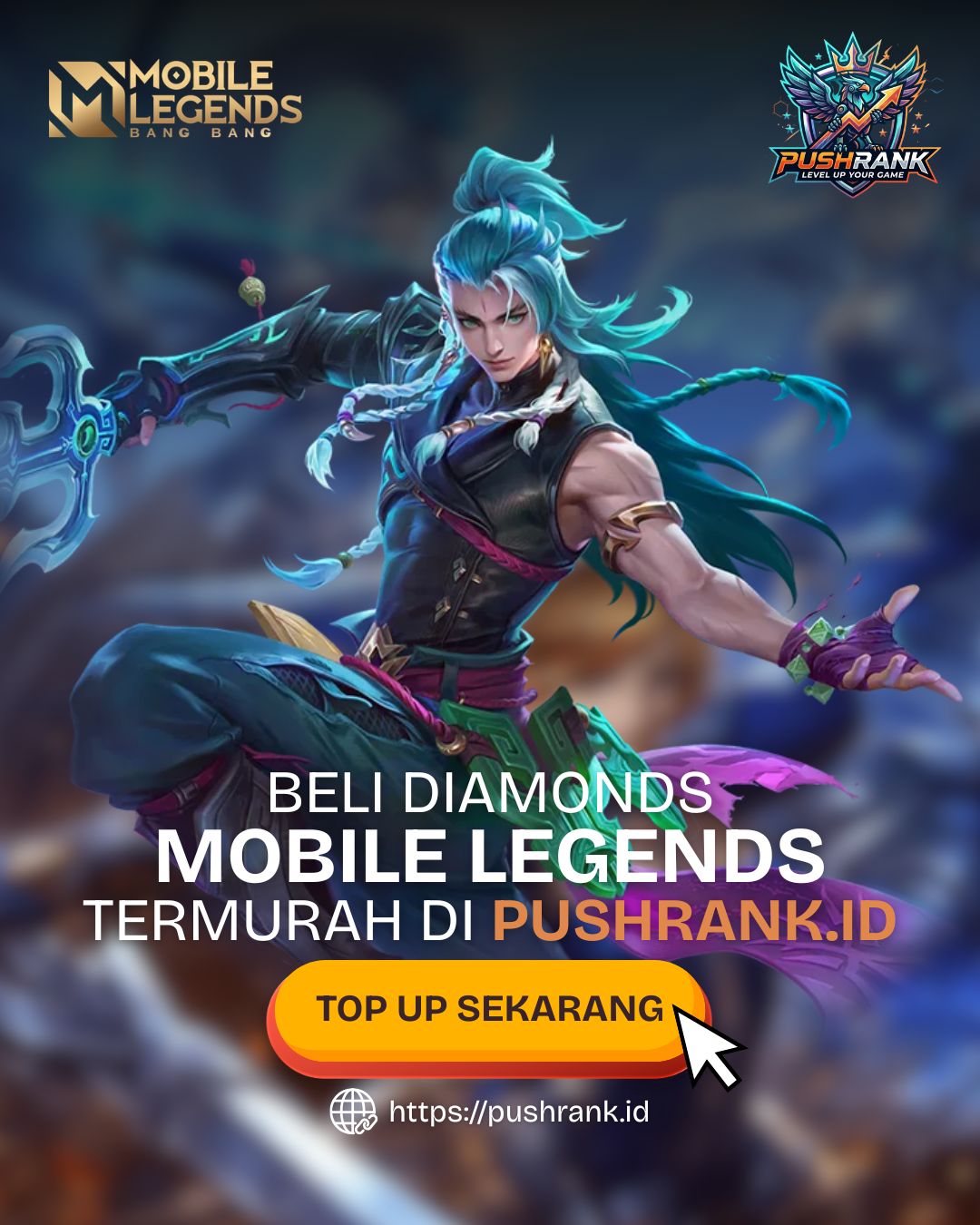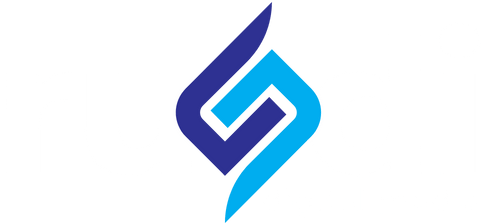Para peneliti memperingatkan bahwa perubahan iklim global dapat menghadapi ancaman serius apabila Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat, menyusul wacana Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah tersebut dan mengeksploitasi sumber daya alamnya.
Peringatan ini menyoroti potensi dampak luas yang tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga ilmiah dan lingkungan. Greenland selama ini menjadi salah satu lokasi riset iklim paling penting di dunia, menyimpan arsip alam yang krusial untuk memahami dinamika pemanasan global dan kenaikan permukaan laut.
Greenland bukan sekadar hamparan es dan salju. Wilayah ini sejak lama menyimpan sumber daya bernilai tinggi yang menarik perhatian dunia. Salah satu contoh historis adalah meteorit Cape York seberat sekitar 58 ton, yang pada 1897 diambil oleh penjelajah Robert Peary dengan bantuan pemandu Inuit setempat, lalu dijual ke Amerika Serikat. Selama berabad-abad sebelumnya, masyarakat lokal memanfaatkan pecahan meteorit tersebut untuk membuat alat berburu, sebelum akhirnya sumber daya itu berpindah dari kendali komunitas setempat.
Kini, ambisi Donald Trump dinilai melampaui sekadar ketertarikan pada artefak sejarah. Wacana pengambilalihan Greenland, bahkan dengan opsi penggunaan kekuatan, dipandang sebagai pergeseran dari pendekatan diplomasi menuju upaya dominasi strategis.
Deputy Vice-Chancellor University of Exeter, Martin Siegert, menilai langkah semacam itu berpotensi menimbulkan konsekuensi besar bagi ilmu pengetahuan global. Menurutnya, pengambilalihan sepihak dapat mengganggu tradisi kolaborasi ilmiah terbuka yang selama ini memungkinkan para peneliti dunia, termasuk dari Amerika Serikat, untuk mengkaji perubahan iklim secara komprehensif.
“Dunia berutang besar kepada Greenland dan Amerika Serikat atas kemajuan ilmu pengetahuan ini, yang dilakukan secara terbuka dan adil. Kerja sama semacam ini harus terus berlanjut,” kata Martin dalam tulisannya di The Conversation.
Secara politik, Greenland memiliki kedaulatan dalam hampir seluruh urusan domestik, kecuali pertahanan dan kebijakan luar negeri yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Dengan demikian, Greenland juga berada dalam payung NATO. Akses ke wilayah darat dan perairannya diatur melalui sistem perizinan yang ketat, termasuk untuk kegiatan penelitian ilmiah.
Selama beberapa dekade, Greenland membuka diri bagi ilmuwan internasional untuk meneliti lapisan es, batuan, dan dasar lautnya. Peneliti dari Amerika Serikat termasuk yang paling diuntungkan, dengan kontribusi besar dalam pengeboran es dalam guna merekonstruksi hubungan historis antara karbon dioksida dan suhu Bumi, serta misi-misi NASA yang memetakan daratan di bawah lapisan es.
Sekitar 80 persen wilayah Greenland tertutup lapisan es raksasa. Jika seluruh es tersebut mencair, permukaan laut global diperkirakan dapat naik hingga sekitar tujuh meter. Pencairan yang semakin cepat akibat pemanasan global juga berpotensi mengganggu sirkulasi samudra Atlantik Utara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas iklim belahan bumi utara.
Sementara itu, sekitar 20 persen wilayah Greenland yang bebas es memiliki luas setara dengan Jerman dan menyimpan potensi mineral besar. Survei geologi menunjukkan keberadaan mineral strategis yang lebih relevan untuk mendukung transisi energi hijau, seperti bahan baku untuk turbin angin dan baterai kendaraan listrik, dibandingkan eksploitasi bahan bakar fosil.
Meski terdapat cadangan batu bara, biaya eksploitasinya dinilai tidak ekonomis, dan ladang minyak besar belum ditemukan. Fokus komersial justru tertuju pada mineral kritis yang dibutuhkan teknologi energi terbarukan. Dengan demikian, Greenland menyimpan dua aset penting sekaligus, yakni pengetahuan ilmiah dan material strategis untuk menghadapi krisis iklim.
Namun, Siegert menilai komitmen Trump terhadap isu iklim relatif lemah. Setelah menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, pada Januari 2026 Trump juga mengumumkan keluarnya AS dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dalam berbagai pernyataannya soal Greenland, Trump lebih menekankan isu keamanan dan akses mineral, dengan minim perhatian pada riset iklim.
Padahal, berdasarkan perjanjian pertahanan tahun 1951 dengan Denmark, Amerika Serikat telah memiliki pangkalan militer di Pituffik, Greenland utara. Selama kedua negara sama-sama berada dalam NATO, AS bahkan dapat memperluas kehadiran militernya sesuai kebutuhan, tanpa harus menguasai Greenland secara sepihak.
Upaya mengamankan Greenland di luar kerangka NATO justru dinilai berisiko merusak perjanjian yang ada, sekaligus mengancam akses ilmuwan global ke salah satu laboratorium alam terpenting di planet ini.
Siegert membandingkan situasi Greenland dengan wilayah kutub lain. Antartika, misalnya, diatur oleh perjanjian internasional yang menjadikannya kawasan damai dan pusat ilmu pengetahuan, serta melarang aktivitas pertambangan. Sementara Kepulauan Svalbard berada di bawah kedaulatan Norwegia, tetapi memiliki sistem internasional yang memungkinkan puluhan negara melakukan aktivitas riset dan ekonomi secara terbatas.
Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Greenland tidak memiliki perjanjian internasional khusus yang menjamin akses ilmiah global. Keterbukaan penelitian di pulau itu sangat bergantung pada stabilitas politik dan kebijakan pemerintahannya, yang dinilai dapat terancam jika berada di bawah kontrol Amerika Serikat.
Secara teoritis, Greenland dapat mengembangkan model kerja sama internasional melalui NATO, yang menggabungkan aspek keamanan, eksplorasi mineral, dan riset ilmiah, tetap di bawah regulasi dan kedaulatan Greenland.
“Pada akhirnya, masa depan Greenland harus ditentukan oleh orang Greenland sendiri, bersama Denmark. Masa depan ilmu iklim dunia dan transisi menuju peradaban global yang aman dan sejahtera juga bergantung pada akses berkelanjutan ke pulau ini, dengan syarat yang ditetapkan oleh masyarakat yang tinggal di sana,” ujar Siegert.
Ia menegaskan, kisah meteorit Cape York yang diambil dari wilayah dekat Pangkalan Luar Angkasa Pituffik menjadi pengingat simbolis bahwa kendali atas sumber daya dan pengetahuan dapat hilang dengan mudah. Kali ini, taruhannya bukan sekadar artefak sejarah, melainkan masa depan iklim Bumi. (***)